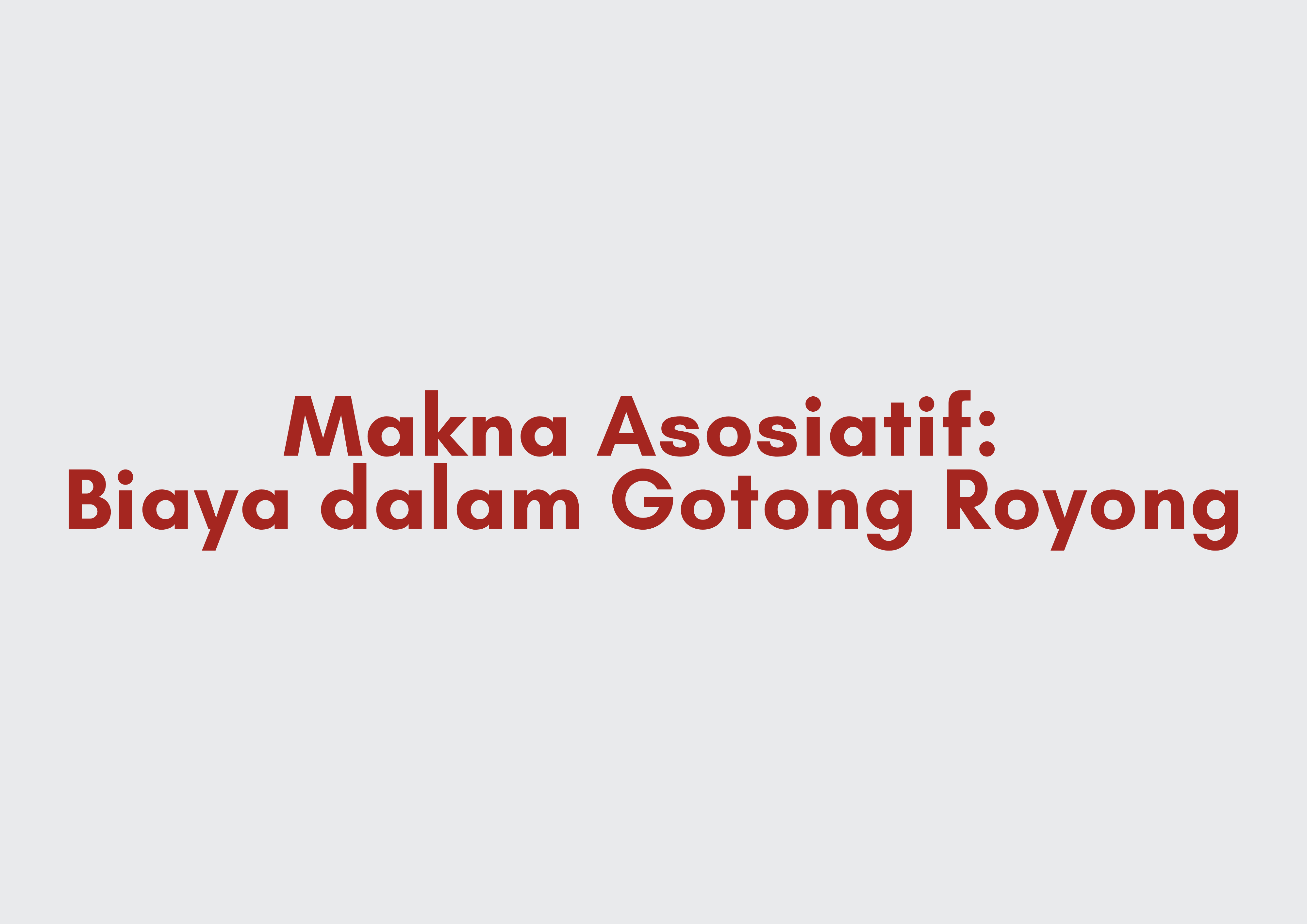Beberapa waktu belakangan, netizen di jagad Twitter murka. Tentu saja apa yang mereka—bahkan saya pun sesekali ikutan—serapahkan berkaitan dengan kondisi Indonesia saat ini. Kita tahu, kurva mortalitas akibat Covid-19 terus meningkat. Ditambah lagi, warganet makin marah ketika program Vaksinasi Gotong Royong dicetuskan.
Agus Noor, seorang penulis, merespons munculnya program tersebut dengan cuitan seperti ini: Yang juga berbahaya, vaksin Gotong Royong berbayar itu akan mendistorsi makna “Gotong Royong” // Gotong Royong = (kini bermakna) Berbayar. Setelah saya pikir-pikir, ia betul juga. Selama ini, saya telanjur memahami bahwa gotong royong berarti menekankan kesukarelaan, sekalipun kata majemuk tersebut sama sekali tidak menyiratkan makna demikian. Gotong royong, dalam kamus kita hari ini, mengartikan ‘bekerja bersama-sama (tolong-menolong, bantu-membantu)’.
Tentu saja pemaknaan saya terhadap gotong royong tidak terlepas dari pengetahuan dan pengalaman pribadi. Barangkali, gotong royong sudah menjelma menjadi semangat bagi anggota kepanitiaan suatu acara di kampus. Rugi bareng, untung pun bareng. Kira-kira seperti itu perwujudan gotong royong yang saya pahami sejauh ini.
Darmojuwono dalam Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik (2005) menulis bahwa pemaknaan kita terhadap kata dapat berangkat dari unsur-unsur di luar bahasa. Pikiran, pengetahuan, dan pengalaman seseorang turut membentuk sebuah makna yang disebut makna asosiatif. Apabila ditarik lebih jauh lagi, makna asosiatif pun berpotensi lahir sebab adanya kesamaan pengalaman, lingkungan, dan latar belakang budaya dalam suatu komunitas.
Dalam bukunya yang berjudul Semantics: The Study of Meaning (Second Edition) (1985), Leech menjelaskan bahwa makna asosiatif dapat mencakup makna konotatif, makna sosial atau stilistika, makna afektif, makna reflektif, dan makna kolokatif.
Sebagaimana yang kita ketahui, makna konotatif berkaitan dengan suatu perasaan yang muncul ketika kita membaca atau mendengar kata. Kita bisa mengasosiasikan kata pete dengan perasaan yang tidak senang karena makanan itu menyisakan bau tidak sedap bagi pelahapnya. Bisa juga, pete berasosiasi dengan perasaan yang menyenangkan karena kelezatannya menambah nafsu makan.
Kemudian, ketika membicarakan perbedaan kata rumah dan vila, kita sedang berada dalam ranah makna stilistika atau sosial. Asosiasi yang mungkin muncul dari kata vila adalah ‘liburan’, ‘gunung’, atau ‘pantai’. Kata rumah mungkin saja menimbulkan asosiasi yang berbeda.
Sementara itu, makna afektif dinilai lebih efektif apabila dikaji secara lisan. Intonasi dan pemilihan kata memiliki peran penting untuk membentuk makna. Pada dua contoh di bawah ini, ada kesan yang berbeda.
- Ini perpustakaan. Tutup mulutmu!
- Ini perpustakaan. Tolong pelankan sedikit suaramu.
Makna yang berikutnya adalah makna reflektif. Terkadang, makna suatu kata merefleksikan pemaknaan yang lain sehingga memicu ketaksaan. Bahkan, Nordquist mengatakan bahwa komedian sering memanfaatkan makna reflektif dalam penampilannya. Coba baca selengkapnya di sini.
Terakhir, makna kolokatif, yakni makna yang muncul ketika suatu kata memiliki sinonim dengan makna kata lain atau keduanya berada pada ranah yang sama. Baca selengkapnya tentang kolokasi di sini.
Lima jenis makna tersebut tidak bisa dilepaskan dari pengetahuan dan pengalaman seseorang atau suatu kelompok. Apa yang diungkapkan oleh Agus Noor, bisa dibilang, berkaitan dengan pengalaman beliau dalam memaknai kata majemuk gotong royong. Jangan-jangan, jika program Vaksinasi Gotong Royong berhasil dan sukses dijalankan, perwujudan gotong royong akan makin sukar untuk ditemukan sebab asosiasi maknanya yang kian ke mana-mana.
Boleh jadi, suatu hari nanti gotong royong berasosiasi dengan perasaan tidak enak, bukan dengan kesukarelaan yang tidak memerlukan uang. Lebih dari itu, kesan tidak enak tersebut saya rasa jauh lebih buruk ketika kita harus urung bergotong royong lantaran biaya yang mahal.
#semantik #makna
Rujukan:
- Chaer, Abdul. 2007. Linguistik Umum. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kushartanti, dkk. (ed). 2005. Pesona Bahasa: Langkah Awal Memahami Linguistik. Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Leech, Geoffrey. 1985. Semantics: The Study of Meaning (Second Edition). Westminster: Penguin Books.
- Nordquist, Richard. 2020. “Definition and Examples of Associative Meaning”. Diakses pada 13 Juli 2021.
- _______________. 2017. “What Is Reflected Meaning?”. Diakses pada 13 Juli 2021.
Penulis: Yudhistira
Penyunting: Ivan Lanin